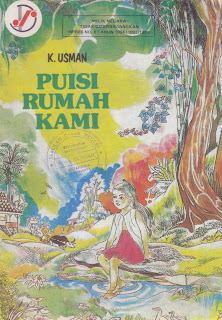Tiada Merah di Hari Terindah
Bandung Mawardi
Jutaan orang di Indonesia pernah dipijami buku
oleh negara. Buku itu terbitan Depdikbud memiliki pesan ke murid: “Buku ini
milik negara. Dipinjamkan kepada murid untuk dibawa pulang! Pelajarilah isinya!
Rawatlah baik-baik! Tahun depan adikmu yang akan menggunakan buku ini.” Kita
sudah lupa pesan dicantumkan di sampul buku bagian belakang. Buku “paket”
diurusi guru dan disimpan di perpustakaan untuk mencerdaskan murid-murid. Buku
dicetak sederhana. Buku dengan gambar di sampul garapan Pak Raden.
Buku itu berjudul Bahasa Indonesia 3c: Membaca (1975). Buku dipinjamkan, mustahil
jadi hak milik. Pengecualian adalah “pencuri” atau orang fanatik dengan
nostalgia SD. Buku mujarab dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional dan
mengesahkan pembangunan nasional. Buku itu pula mungkin memberi sokongan
pengangkatan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Buku pelajaran penting
dalam pengisahan rezim Orde Baru. Buku itu “amal terindah” di masa lalu.
Kita membuka halaman 50-53, cerita berjudul “Kakak
Sudah Kelas Enam”. Keluarga Pak Halim berkumpul di malam hari. Pak Halim
membaca koran. Bu Halim sedang merenda. Tiga anak (Arman, Ima, Adi) sedang
belajar. Duh, keluarga bahagia. Bapak berkata: “Arman, kau sudah kelas enam
sekarang. Beberapa bulan lagi akan tamat dan menjadi murid SMP.” Arman sudah
memiliki sikap-pilihan. Arman menjawab: “Arman tidak mau masuk SMP, Pak. Arman
ingin menjadi tukang kayu. Arman ingin dapat membuat rumah sendiri.” Jawaban
itu mirip dengan keinginan Franz Kafka. Kita telanjur mengenali sebagai
pengarang sangar di dunia. Sejak bocah, ia bercita-cita menjadi tukang kayu.
Eh, Franz Kafka malah menderita dan murung menghasilkan cerita dan novel.
Jadilah ia pengarang, tukang cerita.
Perkataan Arman membuat bapak-ibu tercengang.
Pilihan Arman dihormati melalui penjelasan bermutu: “Bapak setuju, Arman.
Pekerjaan tukan kayu pekerjaan yang baik juga. Bukan asal menjadi tukang kayu
saja, tetapi tukang kayu yang ahli. Untuk itu harus bersekolah dulu di sekolah
teknik.” Arman senang mendapatkan mufakat. Di sekolah, ia memang suka
mengerjakan prakarya atau tugas-tugas kerajinan. Nilai sering tinggi. Ia mantap
melanjutkan ke sekolah teknik, menata diri bakal menjadi tukang kayu. Ia tak
berani kebablasan menjadi presiden. Jawaban dan penjelasan Arman disahuti Irma.
Bocah perempuan masih kelas tiga itu berujar ingin menjadi tukang jahit. Ah,
cerita itu pantas disalin utuh untuk dibagikan ke presiden dan para pejabat
ingin memajukan sekolah-sekolah kejuruan di seantero Indonesia.
Kita pertemukan cerita di buku pinjaman Orde Baru
dengan buku cerita berjudul Kokom Naik
Kelas gubahan Zainuddin Lubis dan gambar-gambar oleh Steve Kamajaya. Buku
terbitan Balai Pustaka, 1977. Tipis, 40 halaman. Gambar di sampul buku
menampilkan ibu dan bocah perempuan berpelukan. Di tangan si bocah, ada buku
rapor. Pelukan menghasilkan bunga-bunga. Kita terkesima. Buku tak memiliki
judul puitis. Judul biasa saja.
Penulis cerita mempersembahkan buku ke anak-anak
tercinta: Chomsiyah, Miftah, dan Adiyan Nur. Mana tiga anak itu tak digunakan
dalam cerita. Zainuddin Lubis malah menamai para tokoh: Nunu, Orba, dan Kokom.
Nama-nama aneh. Nama paling keren adalah Orba. Pengarang mungkin kagum dengan
Soeharto atau rezim Orde Baru. Dulu, kita biasa mendapatkan akronim Orba untuk
Orde Baru. Penamaan Orba diharapkan si bocah bakal pintar dan menjadi presiden.
Ingat Orba, ingat Soeharto.
Kita selingi dulu mengutip masa sekolah Soeharto
dalam buku susunan G Dwipayana dan Ramadhan KH berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989). Pada saat di
sekolah rendah, Soeharto paling pintar di pelajaran berhitung. Ia pun rajin
mengurusi tanaman alias bertani. Ia tak pernah mengalami peristiwa seperti di
buku berjudul Bahasa Indonesia 3c:
Membaca (1975). Soeharto lahir dan tumbuh di keluarga miskin. Situasi itu
mengajari kesabaran, keberanian, dan kesungguhan. Jadilah ia tentara dan
presiden. Ia tak pernah ingin jadi tukang kayu.
Nah, penamaan Orba di buku cerita terasa wajar
untuk meneladani Soeharto. Di situ, Orba masih kecil, belum bersekilah. Orba
suka main gasing. Kita tak tahu nama lengkap Orba. Kita menduga ia bernama
lengkap: Orba Pemnas (Orde Baru-Pembangunan Nasional). Cerita bertokoh utama
Kokom, bukan Orba. Kita jangan cerewet mengurusi Orba. Kokom itu anak sulung,
sudah sekolah. Kokom kelas 2 SD. Kita jangan menuduh ia di sekolah bernama SD
Sukaorba.
Zainuddin Lubis mengisahkan: “Kokom sudah mulai
lancar membaca. Ia sangat senang membaca. Selesai ibunya sembahyang isya,
dilihatnya Kokom sedang membaca komik. Orba dan Nunu duduk di dekatnya. Datang
ibu menghampiri. ‘Kokom, tidak ada pekerjaan rumah?’ Tanya ibu. Kokom berhenti
membaca dan berpikir sebentar, ‘Oh, Kokom hampir lupa.” Kokom lekas bertindak:
mengambil tas, mengeluarkan buku dan alat tulis, merampungkan PR dari
guru. Kokom ingin bertanggung jawab.
Tugas-tugas harus bisa diselesaikan dengan serius.
Kokom lega, PR sudah selesai. Ia masih hampir
lupa. Ibu mengingatkan lagi: “Lalu, pekerjaan jahitan Kokom, sudah selesai?”
Duh, Kokom harus mengurusi tugas jahitan sebelum tidur. Ibu masih melanjutkan:
“Hati-hati, Kokom, sebentar lagi kenaikan kelas, bukan? Kalau kau tak naik akan
disusul adikmu. Apakah kau tak malu.” Kokom berbeda dari Ima. Kokom masih kelas
dua SD, belum berani sesumbar ingin menjaddi tukang jahit seperti Ima. Tugas
itu saja belum berhasil diselesaikan. Gagal mengerjakan tugas bisa berakibat ke
nilai dan kenaikan kelas. Kita membaca kalimat-kalimat ibu itu mengingatkan,
masih jauh dari mengancam atau memberi ketakutan. Unsur mengejek juga tak ada.
Ibu tentu mengerti kondisi kejiwaan Kokom dan memiliki pengharapan bahwa Kokom
sudah mengerti tanggung jawab. Di rumah, peran ibu penting dalam membentuk
pribadi dan memberi sokongan bagi kemajuan akdemik Kokom.
Kita mendapat adegan ibu-anak saat malam. Adegan
tanpa bapak dan adik-adik. Kita bisa memberi tafsir dari gambar, dikuatkan
dengan kalimat-kalimat. Kokom gelisah mengingat rapor kemarin memiliki dua
angka merah: menulis dan prakarya. Ibu mengetahui Kokom melamun. Datang dan
menenangkan. Kokom berucap: “Sekarang saya menyesal, Bu. Kokom takut tidak naik
kelas. Doakan, Bu, Kokom naik kelas.” Kokom hampir menangis di malam sebelum
esok penerimaan rapor di sekolah. Ibu mendoakan dan memberi nasihat.
Pagi datag tapi semalam Kokom tak bisa tidur.
Berangkatlah ia ke sekolah dengan berdebar. Menit demi menit, Kokom masih takut
jika tak naik kelas. Di depan, Pak Guru memberi pengumuman bahwa semua murid
naik kelas. Murid-murid lega, bertepuk tangan, dan mesem. Kalimat di buku:
“Rapor si Kokom tidak ada merahnya lagi.” Kokom bukan murid pintar atau bodoh.
Ia memiliki keinginan naik kelas, belum keinginan mendapat peringkat 1 di
kelas. Di rapor, nilai enam ada 2, nilai delapan ada 3, nilai paling ramai
adalah tujuh. Sampai di rumah, Kokom melapor pada bapak-ibu. Ketakutan sudhah
berlalu. Kokom naik ke kels 3. Hore!
Di hari berbahagia, sekolah mengadakan pesta
mengundang murid dan keluarga. Pesta berisi pentas-pentas. Ada pula orang-orang
berjualan. Nunu minta mainan kursi. Orba minta tas. Ibu membeli sulaman taplak
meja. Bapak dibelikan pipa tanduk. Lho! Pedagang di acara sekolah itu
membahagiakan kaum perokok. Kita jangan marah dan protes. Masa lalu Indonesia
memiliki cerita-cerita berterima dalam percakapan dan pemakluman, tak tergesa
jadi demonstrasi, petisi, atau polemik di media sosial. Pada saat acara resmi,
keluarga itu heboh mendengar pengumuman bahwa Kokom peringkat kedua. Lolos dari
nilai-nilai merah, Kokom memiliki prestasi. Di acara hiburan, Kokom naik ke
panggung membaca puisi bertema ibu. Ia mendapat tepuk tangan dari penonton dan
aliran air mata dari ibu. Hari indah berakhir, keluarga bahagia itu pulang.
Kokom merasa paling bahagia. Berakhirlah cerita dengan indah. Begitu.