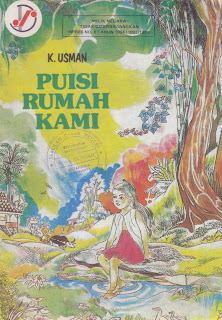Telat dan Tabah
Bandung Mawardi
Gambar di sampul, gambar mendebarkan dan
gampang memberi salah paham. Bocah perempuan, anjing, dan sumur. Bocah itu
berlari ke arah sumur. Di belakang, anjing tampak mengejar. Apakah bocah itu
melintasi sumur atau berhenti di atas bibir sumur? Bocah itu terjatuh ke sumur?
Mengapa anjing itu mengejar? Pilihan gambar di sampul mungkin mengawali
kerancuan pembaca, setelah membaca judul di bagian bawah: Si Kidal. Gambar itu mustahil mampu menjelaskan judul! Gambar
dikerjakan oleh Sulistyo. Di hadapan buku cerita berjudul Si Kidal (1977) gubahan Satmowi terbitan Pustaka Jaya, para pembaca
boleh cemberut duluan sebelum membuka dan menghabiskan 40 halaman.
Buku tipis, buku membikin meringis.
Pengarang membuat tokoh bernama Tribono, dipanggil Kid. Lho! Panggilan
gara-gara Tribono sering mengerjakan pelbagai hal dengan tangan kiri alias
kidal. Resmilah ia mendapat sebutan Kidal, bukan penghinaan. Kidal itu ada di
gambar sampul? Bukan! Tokoh di sampul itu teman Kidal. Judul buku Si Kidal tapi tokoh tak dimunculkan
sejak awal di sampul. Penerbit memiliki kebijakan-kebijakan tanpa harus
menuruti tebakan atau kemauan pembaca. Tribono itu lelaki, bukan perempuan. Di
sampul, bocah berlari itu mengenakan rok. Orang-orang di Indonesia mengenali
lelaki tak terbiasa mengenakan rok untuk sekolah atau lari pagi.
Pengenalan tokoh disampaikan pengarang di
halaman awal, sebelum halaman-halaman cerita. Pengarang ingin pembaca cepat
mengenali karakter tokoh ketimbang di tengah membaca masih saja penasaran.
Gambar si tokoh pun lekas dimunculkan tapi membingungkan pembaca. Ia dikatakan
kidal tapi di gambar Kidal memegang amplop dengan tangan kanan. Ah, kita
terlalu ribut! Buku cerita untuk bocah-bocah SD. Tokoh-tokoh di buku adalah
murid-murid kelas 5 SD di suatu tempat.
Pengarang mengenalkan tokoh: “Namanya Bono,
lengkapnya Tribono. Tetapi kawan-kawannya yang lebih besar memanggilnya ‘Kid’
dan yang lebih kecil ‘Mas Kid’. Dan mereka memanggilnya demikian bukan tanpa
alasan. Itu karena ia lebih banyak mempergunakan tangan kirinya daripada tangan
kanannya. Dan Bono tidak berkeberatan dipanggil demikian. Baginya hal itu bukan
persoalan lagi. Mungkin karena sudah
terbiasa, dan mungkin juga karena ibunya sendiri memanggilnya demikian.”
Bocah pantang minder gara-gara panggilan. Pemberian nama lengkap oleh orangtua
berlaku di formulir atau dokumen resmi saja. Keseharian di rumah dan sekolah,
nama lengkap absen tergantikan Kidal. Bocah itu menerima tanpa protes dengan
menangis dan marah-marah.
Di Indonesia, kita masih memiliki
anggapan-anggapan bereferensi agama dan adat. Sekian orang menganut kesopanan
itu kanan. Penggunaan tangan kanan untuk melakukan sekian hal mengartikan sopan
dan lazim. Sejak kecil, pembiasaan menggunakan tangan kanan diajarkan orangtua
dan guru. Bocah diharapkan saat makan menggunakan tangan kanan untuk memegang
sendok. Perbuatan memberikan sesuatu ke orang lain atau bersalaman tentu
memilih tangan kanan. Belajar menulis dengan pensil pun dianjurkan dengan
tangan kanan. Segala kanan sudah hampir doktrin.
Orang-orang saat melihat bocah memilih
sering menggunakan tangan kiri bakal memberi peringatan atau kemarahan. Mereka
anggap penggunaan tangan kiri itu “jelek” alias “tak sopan”. Memandang orang
mengerjakan sesuatu dengan tangan kiri menimbulkan keanehan. Sangkaan-sangkaan
diberikan sering merendahkan, bukan memberi tenggang rasa. Kiri itu bermasalah.
Tuduhan orang-orang itu gampang disangkal jika membaca buku berjudul Ragawidya garapan YB Mangunwijaya. Sejak
mula, tangan itu bergerak dan bermakna untuk hidup dengan kemuliaan, kebaikan,
dan kebersamaan. Tangan memiliki hak menunaikan ibadah, kerja, atau perbuatan
mendasarkan pada misi-misi manusia mengerti Tuhan, alam, dan sesama. Kidal
belum pernah membaca Ragawidya tapi
mengerti kecenderungan memilih tangan kiri tak harus dinilai keburukan, aib,
dan dosa.
“Keburukan” Kidal bukan di tangan tapi
kegagalan mengerti waktu. Ia itu bocah telatan.
Ingat, telatan, bukan teladan! Ia
sering terlambat ke sekolah. Guru rajin marah. kidal rajin lupa dengan pesan
guru. Hukuman demi hukuman diberikan agar Kidal tobat. Hukuman dan
tawa-mengejek teman-teman tak mempan. Kidal tetap saja terlambat atau telat
tanpa merasa terlalu bersalah. Keburukan itu sulit dihapus dalam hitungan hari.
Kidal mengaku salah tapi selalu kehilangan pegangan waktu dalam ikhtiar
mengubah kebiasaan. Guru pernah berpesan ke Kidal berkaitan teladan, bukan telatan: “Gurunya sudah sering berkata
kepadanya bahwa sebenarnya ia dapat menjadi anak teladan, seandainya ia mau
sedikit berusaha dan menghilangkan sifat malasnya.” Duh, bocah telatan gagal teladan. Kidal itu bukan
murid pintar. Eh, pengarang tetap mengisahkan Kidal memiliki kebaikan,
keampuhan, dan kehormatan.
Di mata teman-teman, Kidal itu sering
membuat sebel dan ngangeni. Di depan kelas, Kidal pasrah
saat dimarahi guru: “Sudah lebih tiga kali dalam minggu ini kau datang
terlambat ke sekolah. Dan untuk selanjutnya, bila kau tetap juga datang
terlambat maka kau dilarang memasuki ruang kelas.” Kidal tanpa pembelaan. Satu
kata tak terucap. Ia memang bersalah. “Matanya dan bibirnya bergerak seperti
mau berkata, tetapi tak jadi,” tulis Satmowi. Kidal itu lugu tapi ndablek.
Ia harus pergi dari kelas. Hukuman agak
berat! Di hati, ia ingin belajar bersama teman-teman, dari pagi sampai siang.
Di sela pelajaran atau waktu istirahat, Kidal ingin bermain girang bersama
teman-teman. Angan tak kesampaian. Ia harus pergi. Pulang ke rumah tak enak.
Kidal berjalan tanpa tujuan jelas. Sampailah ia ke pasar! Menit-menit pun cepat
berlalu. Ia sempat menonton pentas sandiwara digelar penjual obat di pasar.
Kidal atau Bono sudah hapal dengan sandiwara sering membuat orang-orang tergoda
membeli obat. Duh, obat tanpa resep dokter. Obat membatalkan seruan: “obat bisa
dibeli di toko terdekat”.
Di situ, Kidal berbuat kebaikan. Ada bocah
tersesat, terpisah dari orangtua. Orang-orang ribut dan saling usul tanpa
tindakan. Kidal mendekati si bocah. Eh, Kidal melihat bocah itu memegang
kertas. Kertas itu amplop surat. Kidal dengan sopan meminta dan membaca tulisan
di situ. Di bagian belakang, terbaca alamat pengiri. Kidal menduga pengirim
adalah ibu si bocah tersesat. Kidal tak memerlukan setengah jam untuk berpikir.
Bocah itu lekas diantar pulang sesuai alamat di amplop. Selamat! Bocah itu
sampai rumah. Pada hari buruk terusir dari kelas, Kidal masih mungkin berbuat
kebaikan: menjadikan hari tetap bermakna.
Sial masih milik Kidal di keesokan hari. Ia
berhasil sampai sekolah tanpa telat. Aduh, ia diminta lagi berdiri di depan
kelas. Deskripsi dari pengarang: “Keesokan harinya, Bono disuruh lagi berdiri
di muka kelas karena tak membuat pekerjaan rumah. Pak Iwan tak mau menerima
alasan bahwa ia tak mengerjakan pekerjaan rumah itu karena ia kemarin disuruh
pulang. Ia tak tahu bahwa ada pekerjaan rumah dan ia pun tak menanyakan pada
teman sekelasnya.” Sekolah itu sumber sial bagi Kidal. Ia sulit “benar” dan
“baik”. Di jalanan dan pasar, Kidal malah sanggup membuat keputusan dengan
dalil-dalil kebaikan tanpa kaidah seperti di buku pelajaran atau khotbah guru.
Di kelas, Kidal adalah murid kalahan,
korban ejekan dari teman-teman, terutama Tunggadewi. Pembaca mungkin terharu
mengikuti cerita Kidal. Empati pantas diberikan agar Kidal bertahan hidup dalam
cerita. Pada suatu hari, Kidal berhasil menghuni kelas tapi “merana”. Ada
sedikit peristiwa perbantahan antara Tunggadewi, Kidal, dan teman-teman. Kidal
pasti kalah. Satmowi menulis: “Kidal tahu ia selalu kalah kalau harus berperang
mulut dengan Tunggadewi. Tak seorang pun yang mampu mengalahkan Tunggadewi
dalam berperang mulut dan saling ejek. Semua anak-anak tertawa ketika
Tunggadewi berkata, ‘Sana masuk saja ke dalam kelas dan menggambar kepala
wayang.’ Anak-anak bertepuk riuh ketika Kidal benar-benar masuk kelas dan
menggambar kepala Dorna di papan tulis.” Ah, bocah itu tak mau melawan untuk
meraih menang meski sekali saja. Pengarang keterlaluan dalam penokohan Kidal!
Kita malah penasaran dengan kekalahan Kidal. Kalah dimaknai dengan menggambar
tokoh wayang. Mengapa ia memilih tokoh Dorna dalam epos Mahabharata?
Hari demi hari di sekolah, Kidal terus
kalah. Ia malu menangis atau mutung. Kalah itu lumrah. Pilihan menikmati
kekalahan membuat Kidal menjadi bocah paling tabah. Ia menganut tawakalisme! Pada
suatu musim bermain layang-layang, Kidal mengajak Hadi berdagang layang-layang.
Perbuatan mendapat untung. Kebahagiaan dua bocah itu mendapat gangguan dari
Tunggadewi. Adegan “perampokan” terjadi di kelas. Tunggadewi memaksa Hadi
memberikan duit untuk membeli jajanan bakal dibagikan ke teman-teman.
Ah, lelaki jadi korban permainan kata
Tunggadewi: “Yang penting kau sekarang sudah menjadi salah seorang pengusaha
layang-layang. Bukan maksud kami agar kau membelikan kami makanan, atau kau
bagi pula kami. Samasekali bukan. Tetapi ada baiknya juga kau mengetahui bahwa
kami kini telah mengantuk. Kantuk mungkin dapat kami tahan, tetapi pelajaran
terakhir pasti akan sukar dapat kami tangkap. Kau tahu sendiri orang mengantuk
dan setengah lapar itu biasanya sukar sekali untuk dapat menerima pelajaran,
bukan.” Ribuan kalimat, eh, puluhan kalimat diucapkan Tunggadewi mengandung
ancaman dan muslihat. Tunggadewi menang merampok Hadi. Kidal atau Bono
mengetahui tapi memilih diam. Ia tetap saja menggambar kepala Begawan Dorna.
Kalimat-kalimat terindah dari Tunggadewi
menjadikan aksi merampok itu puitis dan bijak. Kidal menguping saja omongan si
pemenang kepada Hadi setelah memberikan duit: “Kau memberikannya dengan ikhlas
atau tidak, kami tidak tahu. Tetapi kami tahu bahwa seseorang yang memberikan
sesuatu tanpa disertai hati yang ikhlas adalah orang paling tak berbahagia.
Semoga engkau memberikannya dengan hati yang ikhlas dan aku akan menerimanya.
Terima kasih, demikian juga teman-teman lainnya. Kau telah mengusir rasa kantuk
dan rasa lemas kami...” Pengarang sungguh mahir memberi bahasa ke tokoh. Di
aksi perampokan, ajaran bijak disampaikan seperti dituturkan oleh orang dewasa.
Pembaca sempat terpukau. Hadi dikalahkan tapi mendapat nasihat bijak.
Pada menit berbeda saat murid-murid pulang,
Kidal berjalan bersama Hadi. Perampokan itu membuat teman-teman sekelas girang.
Hadi merasa bersalah tiada terkira. Di perjalanan pulang, ia menunduk lesu dan
malu. Kidal ingin memulihkan keadaan. Berkatalah Kidal dengan santun untuk
sahabat alias pasangan dalam bisnis menjual layang-layang: “Hadi yang malang,
kau telah dirayu olehnya. Tunggadewi adalah seorang perayu yang ulung. Jangan
lupa itu. Anggap saja kejadian ini sebagai pelajaran bagimu...” Kidal dan Hadi,
dua bocah dikalahkan Tunggadewi. Mereka tabah alias senasib sepenanggungan.
Mereka tak marah atau ingin membalas dendam. Nasib sial diterima tanpa sambat
dengan kata-kata bisa ditata meninggi sampai ke langit. Pembaca mulai mengerti
bahwa buku itu tak melulu bercerita Kidal tapi memberi kejutan dengan
pengisahan Tunggadewi. Penjudulan mungkin salah, setelah salah memasang gambar
di sampul. Begitu.