Berkisah Rumah,
Petuah ke Bocah
Bandung Mawardi
Umat sastra di Indonesia mengingat buku puisi Amir
Hamzah, Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar, Rendra, Ajip Rosidi, Sapardi
Djoko Damono, Taufiq Ismail, Goenawan Mohamad, Sutardji Calzoum Bachri, Zawawi
Imron, Afrizal Malna, Oka Rusmini, Joko Pinurbo, dan lain-lain. Sekian orang
sulit mengingat buku puisi berjudul Puisi
Rumah Kami (1984). Buku tipis tapi manis. Buku terbitan Danau Singkarak
semakin sulit dimengerti umat sastra gandrung buku puisi. Mereka ingat penerbit
buku puisi adalah Balai Pustaka, Pembangunan, Pustaka Jaya, Bentang, Gramedia Pustaka
Utama, dan lain-lain.
Buku itu berisi 30 puisi gubahan K Usman. Di
kalangan sastra berumur tua, K Usman itu pengarang penting untuk bacaan bocah
dan dewasa. Puluhan buku sudah ditulis dan terbit. Puisi Rumah Kami itu bacaan untuk bocah. Pada 1984, buku itu
mula-mula diterbitkan Cypress mendapatkan penghargaan buku terbaik bidang puisi
oleh Yayasan Buku Utama. Kalimat resmi dari Yayasan Buku Utama kepada K Usman:
“Kami mengucapkan selamat atas hasil karya saudara. Yayasan Buku Utama akan
memberikan kepada saudara hadiah berupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dan piagam penghargaan. Penyerahan hadiah akan diberitahukan kemudian.
Semoga putusan Yayasan Buku Utama ini dapat saudara terima dengan ikhlas dan
gembira.”
Lembaran resmi memang dipasang di buku Puisi Rumah Kami. Dokumentasi di
kehormatan K Usman sebagai pengarang puluhan buku bocah. Ketekunan dan capaian
membuktikan pengadaan bacaan anak memang harus bermutu dan berkesinambungan. K
Usman mendapat hadiah diberi pesan agar “ikhlas dan gembira”. Kita mengandaikan
hadiah itu menghidupi. Duit dan piagam memberi rangsangan membesar dalam
penulisan lagi buku-buku beredar di seantero Indonesia melalui Inpres atau
penerbit partikelir di jalur umum. Buku mengakibatkan gembira, bukan keluhan
setinggi pohon kelapa. K Usman tak cuma sekali mendapat penghargaan. Ia pantas
dihormati dan tercatat di ensiklopedia bacaan anak Indonesia. Ia adalah pemberi
petuah rumah ke bocah.
Tiga puluh puisi untuk bocah, tak pantas
dibandingkan dengan puisi-puisi gubahan para pujangga legendaris dibaca kaum
dewasa. Kita menduga taka da sebiji puisi di buku berjudul Puisi Rumah Kami dipilih untuk lomba-lomba deklamasi tingkat SD,
dari masa ke masa. Panitia sering memilih puisi “dewasa” dipaksa dibaca oleh
bocah-bocah tanpa mengerti maksud atau kesesuaian selera-tingkatan berbahasa. Puisi-puisi
gubahan K Usman “enak” terbaca dan tak merepotkan pembaca dalam mengerti pesan
atau bujukan imajinatif. Ia bukan pujangga mendadak tapi memiliki kaidah-kaidah
dengan kesadaran bakal jadi bacaan bocah.
Puisi-puisi berpusat di rumah. Pilihan tempat itu
mengembalikan pengalaman dan pemaknaan rumah. Pengindahan terjadi di puisi.
Kita simak puisi berjudul “Tanaman Penting di Sekeliling Rumah.” K Usman
membuat kita cemburu ingin memiliki rumah indah: Cabai, kunyit, dan serai/ Ditanam ibu di belakang rumah/ Singkong,
ketela, dan papaya/ Ditanam ayah di kebun tengah// Adik memelihara melati di
sisi pagar/ Setiap pagi bunganya mekar/ Aku menanam mawar di kebun kiri/
Harumnya semerbak pagi hari. Keluarga bertanam untuk pangan dan
pemandangan. Keren! Puisi mengingatkan sindiran Frits W Went dalam buku
berjudul Tetumbuhan (1982): “Sayang,
makin tinggi peradaban kita, makin jauhlah kita dengan tetumbuhan, dan makin
kaburlah pengetahuan kita mengenai botani. K Usman masih mengisahkan rumah dan
tanaman, kisah sulit mewujud di masa sekarang. Rumah-rumah abad XXI cenderung
tak lagi membuat makna bersama tetumbuhan.
Tema terlupa saat bacaan bocah “terperintahkan”
harus mengandung pesan moral. Puisi-puisi gubahan K Usman menuntun pembaca
menuju rumah. Perbedaan bentuk atau tampilan rumah dengan pembaca memberikan
dalih mengerti kebermaknaan rumah di Indonesia dalam urusan arsitektur,
sosiologi, religiositas, ekologi, ekonomi, dan lain-lain. Rumah dalam buku K
Usman mungkin berada di Jawa. Rumah memiliki pengertian bertopang adat. Rumah
bukan sekadar bangunan. Bocah-bocah membaca puisi-puisi mengenai rumah bakal
termenung, terkejut, dan terkesima.
Puisi berjudul “Jendela” terbaca sederhana tapi mengejutkan
bagi bocah mulai disuguhi gambar rumah-rumah khas pengaruh Eropa di buku
pelajaran atau pengamatan melihat rumah-rumah di desa dan kota masa Orde Baru
mulai meninggalkan ajaran leluhur. Rumah di puisi itu terceritakan melalui
jendela: Empat jendela dipasang tukang/
Di sebelah kiri rumah/ Semua menghadap ke matahari pagi/ Bukan tak ada
maknanya, kata ayah/ Sebab, dari sana mengalir rezeki// Empat jendela dipasang
tukang/ Di sebelah kanan rumah/ Semua menghadap ke matahari senja/ Sebab, dari
sana kami menyaksikan/ Bola dunia kembali ke balik bumi. Dua bait memberi
pelajaran baik. Ingat, bukan melulu moral! Penghuni rumah membentuk pengertian
dengan jendela: jumlah dan arah. Pembaca juga terhindar dari kalimat sudah
menjemukan berkaitan jendela dan buku-ilmu. Jendela itu pengajaran ke bocah
jangan selalu dikaitkan slogan telah usang.
Puisi mengajak bocah menugasi diri membuka dan
menutup jendela. Peristiwa rutin harian itu diimbuhi keinginan membuat makna
dari tatapan ke matahari, pohon, langit, binatang, dan lain-lain. Di jendela,
bocah merasakan angin, waktu, dan suasana. Di situ, ia mengalami dengan
keluguan. Bocah di jendela belum tentu kelak bakal jadi penulis puisi, novel,
dan lirik lagu. Lakon mutakhir mungkin membuat bocah kehilangan pengalaman
berjendela. Di sekian rumah gagah dan sangar, jendela sering ditutup rapat.
Jendela dimengerti jalan kedatangan debu dan angin membikin sakit.
Di luar rumah, pembatas atau pagar dibuat dari
bambu. Keluarga itu tak memiliki duit membuat pagar dengan batu bata atau besi.
Pilihan ke bambu pun bijak menuruti kemauan manusia dan alam. Puisi berjudul
“Pagar Bambu”, puisi mengingatkan agar membangun pagar jangan boros dan
menghalangi bertetangga. Pagar di abad XXI malah membuat rumah itu mirip
penjara. Pagar tinggi dan menutup pemandangan sengaja merusak wajah rumah dan
menuduh ke orang-orang bakal jadi pencuri.
K Usman menulis: Pagar bambu, kuning dan kukuh/ Bambu disebut juga buluh/ Bambu tumbuh
di dalam kebunku/ Bambu melindungi rumahku// Dari pintu kulihat rumpun bambu/
Rimbun daun meneduhkan halamanku/ Akar-akarnya mengukuhkan tanahku/ Rebung atau
bambu muda disayur ibuku/ Bambu, aku berterima kasih kepadamu. Puisi bersahaja
mengabarkan manusia dan bambu bersekutu di desa subur dan damai. Di desa,
pagar bukan kesombongan atau dalih menutup diri penghuni rumah dalam pergaulan
sosial. Kini, orang sengaja membuat pagar-pagar pamer ketakutan, kebebalan,
kesombongan, dan kebrengsekkan. Puisi gubahan K Usman itu ingatan.
Kita tambahi dengan membaca puisi gubahan
Sindhunata berjudul “Ngelmu Pring” dimuat dalam buku Air Kata-Kata (2003). Puisi berbahasa Jawa mengisahkan bambu atau pring, renungan enteng tapi penting: Pring padha pring/ Eling padha eling/ Eling
dirine/ Eling pepadhane / Eling patine/ Eling Gustine. Bermula dari bambu,
manusia merenungi diri, sesame, kematian, dan Tuhan. Puisi itu pernah terdengar
gara-gara disajikan oleh Jogja Hip Hop Foundation. Faedah bambu: lincak asale pring/ pager asale pring/ usuk
asale pring/ cagak asale pring/ gedhek asale pring/ tampar asale pring/ kelo
asale pring/ tampah asale pring/ serok asale pring/ tenggok asale pring/ tepas
asale pring. Bambu menjadi apa saja digunakan dalam kehidupan kita di
keseharian.
Religiositas (di) rumah dirasakan pembaca saat
menikmati puisi berjudul “Tikar Sembahyangku”. Di samping puisi, sehalaman
berisi gambar ibu dan bocah perempuan sedang menunaikan salat. Gambar buatan
Ipe Maaruf. Kita memilih membaca puisi ketimbang menikmati ilustrasi. Kata-kata
sanggup bercerita. Suasana religius terhubung ke kebersamaan keluarga. Kita
sampai ke puisi berjudul “Ruang Keluarga”. K Usman mengajukan keluarga
sederhana dengan rumah tak sesak oleh benda-benda. Rumah belum memiliki meja
dan kursi. Kita membaca: Di ruangan ini
kami makan bersama/ Di ruangan ini kamu duduk bersila/ Sebab rumah kami belum
mempunyai/ Kursi untuk ruangan ini/ Kami duduk sama rendah di sini/ Di atas
pandan anyaman ibu kami. Tikar khas milik keluarga tak berkelimpahan duit.
Kini, tikar itu klasik. Di rumah-rumah abad XXI, kita mulai melihat karpet
menggantikan tikar dibuat dari tetumbuhan.
Puisi sosiologis disodorkan K Usman berjudul
“Tetangga”. Puisi penting diajarkan di sekolah dan rumah. Bocah memerlukan ilmu
tetangga, sebelum ia mengurung diri di rumah: menonton televisi dan bermain
gawai. Puisi dari masa lalu tentu sulit memikat ke pembaca masa sekarang.
Pengisahan K Usman: Tetangga mendengar
denting piring kita/ Tetangga melihat pintu dan jendela kita/ Tetangga
mengetahui masalah gawat kita/ Kita dan mereka tak mungkin berpisah// Tentang
tetangga sebaiknya dikenang-kenang/ Pada mereka kita berbagi susah dan senang/
Dengan tetangga sebaiknya berbagi rasa/ Pada mereka kita titipkan suka dan
duka. Peneliti asing atau ahli Indonesia bisa mengutip puisi “Tetangga”
untuk mengerti kehidupan sosial di Indonesia abad XXI. Makna tetangga perlahan
berkurang oleh pelbagai hal. Tetangga itu masalah besar dalam sosiologi masih
diajarkan di sekolah dan universitas.
Kita akhiri pengembaraan ke halaman-halaman buku K
Usman. Puisi terakhir terbaca berjudul “Puisi Rumah Kami”. Puisi memuncak ke
makna rumah, melegakan bagi pembaca: Rumah
Kami sederhana saja/ Sekitarnya pohon-pohon berbuah/ Sekitarnya bunga-bunga
merekah/ Di atasnya burung-burung terbang merdeka. Bait terbaca di halaman
terakhir, halaman 70. Kita menganggap buku itu penting banget dicetak ulang
oleh Gramedia Pustaka Utama atau komunitas kecil, berharapan ada pengajaran
rumah ke bocah-bocah mulai jarang di rumah gara-gara sekolah dan semakin tak
memiliki makna rumah. Buku itu membikin cemburu. Begitu.
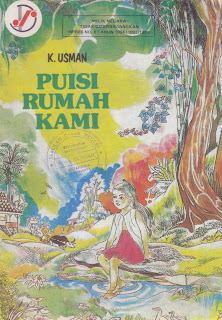

No comments:
Post a Comment